Kritik Atas Konsep Ruang Publik ala Jurgen Habermas
 | |
| suasana diskusi |
Halooo kawan-kawan!
Kali ini aku akan berbagi pengalamanku ketika ikut diskusi
mengenai narasi kritik pemikiran Jurgen Habermas tentang ruang publik yang
ideal. Diskusi ini dihelat di markas Suara Kita, organisasi yang mengadvokasi
hak-hak LGBT. Diskusi berjalan menarik bersama narasumber Dewi Candraningrum.
Jurgen Habermas di tahun 1962
mengajukan konsep Strukturwandel der Offentlichkeit yang menekankan bahwa
negara demokrasi yang sehat dipengaruhi oleh ruang publik yang sehat. Ruang
Publik oleh Habermas didefinisikan sebagai berkumpulnya orang-orang untuk
berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Mula-mula, ruang publik muncul ketika
orang-orang borjuis berdiskusi tentang sastra, politik di kedai-kedai kopi di
Prancis.
 |
| Buku Narasi Kritik Pemikiran Jurgen Habermas |
Dewi Candraningrum dengan
kerangka teori feminisnya mengkritik konsep Habermas tersebut. Bagi Dewi,
Habermas adalah seorang filsuf yang buta gender. Habermas lupa memikirkan
tentang yang liyan di ruang publik. Ruang publik tidak menyediakan keadilan dan
kesetaraan yang sama bagi perempuan, dan kelompok gender ketiga untuk ikut
berpatisipasi aktif dalam ruang publik tersebut.
Narasi kritik tersebut ditulis
dengan begitu lugas, tanpa keragu-raguan. Kalimat demi kalimat tersusun rapi
dalam buku yang ia tulis tersebut. Diksi yang dipakai mencerminkan pemikiran
Dewi Candraningrum yang selalu curiga atas ketidakadilan yang terjadi yang
mungkin saja tidak banyak disadari oleh publik. Dewi mengajukan begitu banyak
pertanyaan pada konsep ruang publik ala Habermas ini. Ia lebih lanjut, menarik
konsep Habermas dari Prancis ke Indonesia dengan mencontohkan tentang Hik-Hik
dan Omah-Omah Wedangan di Solo.
Di sisi lain, Dewi Candraningrum
juga mengkritisi tidak adanya budaya membaca yang kuat di dalam masyarakat
Indonesia. Masyarakat nir-literasi semakin membuat konsep ruang publik Habermas
terasa utopis! Masyarakat Indonesia terbiasa mencari informasi lewat kotak
televisi. Kotak televisi digambarkan oleh Dewi sebagai kotak-kotak paling
nestapa yang mengalami modus-modus eksploitasinya.
Membangun budaya membaca yang
kuat untuk manusia Indonesia bukanlah perkara mudah memang, tapi tentu bukan
pula hal yang mustahil. Tidak adanya budaya membaca dapat kita telusuri
jejak-jejak sejarahnya. Mesin cetak pertama kali ditemukan abad ke 15, bersama
dengan mulai invasi masyarakat Eropa ke Asia. Surat kabar pertama di Indonesia
ada di abad ke 19, itu pun di awal-awal ditulis dalam bahasa Belanda. Ketika
Surat kabar mulai dibaca, saat itu lahir pula radio dan televisi.
Yang menarik juga dari buku ini adalah fakta
bahwa kita tidak hanya akan membaca pemikiran Dewi Candraningrum seorang. Buku
ini juga menyajikan 3 tulisan lagi dari 3 penulis yang berbeda, yang
masing-masing berangkat dari pemikirannya sendiri-sendiri dalam melihat ruang
publik ala Habermas ini. Angelika Riyandari misalnya, Ia menitikberatkan
tulisannya pada majalah wanita. Angelika mengkritisi majalah wanita yang isinya
lebih banyak tentang peran-peran domestik seorang perempuan. Konsep masyarakat
literasi yang mengharuskan masyarakatnya memiliki budaya membaca yang kuat
sebagai prasyarat dari ruang publik yang sehat akan semakin sulit terwujud bila
majalah wanita yang segmentasi utamanya adalah wanita tidak menyajikan isu-isu
kritis.
Coba deh perhatiin isi dari majalah wanita, pastikan tidak
jauh-jauh dari isu-isu domestik dan iklan. Sepertinya tidak ada majalah wanita
yang mengangkat tentang isu-isu kritis seperti angka kematian Ibu saat
melahirkan, isu kekerasan seksual, kepemimpinan perempuan, poligami, dll.
Secara umum, Dewi melalui buku
ini mengajak kita untuk selalu mencurigai ketidakadilan-ketidakadilan yang
dialami oleh yang liyan yang sering kali tersamar. Walau pada akhirnya, Dewi
Candraningrum juga mungkin lupa mencurigai tentang motif pengajuan konsep ruang
publik ala Habermas ini. Jangan-jangan Habermas tidak sedang lagi menggambarkan
realita, tetapi ingin menggambarkan tentang cita-cita. Para penulis juga pada
akhirnya tidak memasukkan unsur entitas kesukuan sebagai yang liyan. Penulis
membatasi diri pada unsur gender untuk menggambarkan yang liyan.
Akhir kata, selamat membaca,
selamat menelaah, dan selamat berpikir apa itu ruang publik, sudahkah kita
menjadi aktor utama di ruang publik, atau kita ada yang liyan?
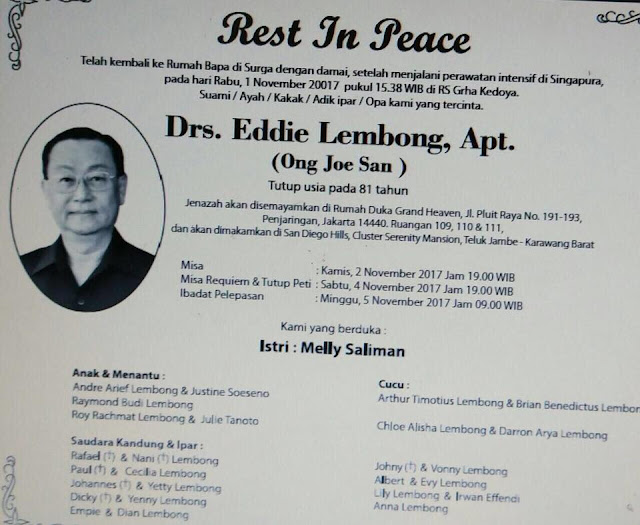


Komentar
Posting Komentar